Filsafat Ilmu
Hal yang paling mendasar yang perlu
diketahui bahwa filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemology, yakni suatu
cabang filsafat yang berbicara mengenai hakikat dari ilmu pengetahuan itu
sendiri.[1] Ketika ingin mencari suatu
dasar, dan ingin mencari suatu pijakan dalam menganalisis suatu ilmu, maka
diperlukan pengetahuan awal yang berkaitan dengan suatu ilmu itu sendiri. Oleh
karena, kita hidup dalam suatu zaman yang sudah terkonstruksi dari segi budaya,
proses berpikir, bertingkah laku, dan sebagainya. Terkadang apa yang sudah kita
yakini sebagai hal yang mutlak dan benar, merupakan hal yang benar adanya,
tanpa memikirkan terlebih dahulu hal tersebut dari prinsip ilmu yang lain.
Mikhael Dua menyatakan bahwa filsafat ilmu pengetahuan tidak lagi bersifat
empiris sebagaimana diusahakan ilmu-ilmu empiris, melainkan bersifat normatis
kritis.[2] Artinya,
Van Peursen menyatakan bahwa Ilmu
pengetahuan dapat dilihat sebagai suatu sistem yang jalin menjalin dan taat
asas (konsisten) dari ungkapan-ungkapan yang sifat benar-tidaknya dapat
ditentukan.[4]
Dengan mendasari pada pemikiran Van Peursen, maka saya melihat bahwa suatu ilmu
pengetahuan tidak bisa terlepas dari suatu etika yang menjadikan sesuatu itu
lebih subyektif, tidak melihatnya sebagai sesuatu yang obyektif. Etika ilmu
pengetahuan diperlukan untuk menelusuri lebih dalam perkembangan ilmu
pengetahuan itu sendiri, ditinjau dari konteks ruang dan waktu yang semakin
lama terbagi dalam beberapa dimensi lintas ilmu. Meninjau dari segi religi dan berbicara mengenai agama,
maka sudah seharusnya agama dimanapun konteks ruang dan waktunya harus bersifat
lebih terbuka, lebih bisa merefleksikan dirinya sendiri, dan pada akhirnya
harus merubah diri untuk menjadi lebih masuk akal.[5] Pengertian masuk akal
dalam pernyataan Betrand Russel yang dikutip oleh Mikhael Dua, menurut
pandangan saya bahwa agama perlu melihat
dirinya hadir dan berada di tengah-tengah dunia ini sebagai sesuatu yang
penting, dan berkaitan dengan etika maupun nilai-nilai yang berada di dalam
suatu masyarakat. Ketika agama ingin melihat dirinya sebagai sesuatu yang berada
di dalam masyarakat, agama perlu merefleksikan ke dalam dirinya, apakah agama
yang selama ini didengang-dengungkan bersifat eksklusivisme terhadap dirinya
dan orang disekitarnya sehingga pada akhirnya melupakan tugas dan panggilannya
hadir di dunia ini, sebagai pembawa nilai-nilai moral di dalam kehidupan
manusia. Agama tidak harus dan tidak melulu berbicara mengenai spiritualitas,
melainkan langsung mendasar pada kebutuhan awal manusia, yakni di dalam
kehidupan sosial yang berkaitan dengan nilai dan norma itu sendiri.
[1]
Suriasumantri, Jujun S, Filsafat Ilmu:
Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, 2007. 33.
[2] Dua,
Mikhael, Filsafat Ilmu Pengetahuan:
Telaah Analitis, Dinamis dan Dialektis, Penerbit Ledalero, 2007. 5.
[3]
Dua, Mikhael, Filsafat Ilmu Pengetahuan:
Telaah Analitis, Dinamis dan Dialektis, Penerbit Ledalero, 2007. 6.
[4] Peursen, Van. Susunan Ilmu Pengetahuan. Gramedia Pustaka, Jakarta. 4.
[5]
Dua, Mikhael, Filsafat Ilmu Pengetahuan:
Telaah Analitis, Dinamis dan Dialektis, Penerbit Ledalero, 2007. 8.


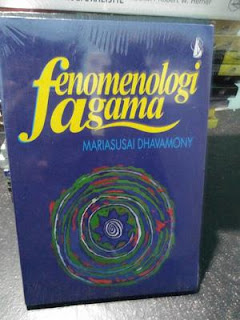
Comments
Post a Comment