PERAN GEREJA DALAM PEMBARUAN POLITIK YANG SUCI DI INDONESIA
PENDAHULUAN
Sejak
kemerdekaan Indonesia 19 Agustus 1945, dari masa ke masa gereja-gereja di
Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari pergolakan politik yang terjadi.
Dapat dilihat dari masa revolusi, pada masa kepemimpinan Soekarno, dan terakhir
yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru pada masa kepemimpinan Soeharto. Di
dalam masa itu menyebabkan munculnya pemikiran serta aspirasi politik yang baru
di kalangan semua kelompok politik. Kejatuhan Soeharto telah memicu gerakan
besar di Indonesia, yang ditandai oleh krisis besar-besaran dan bersifat
nasional. Krisis yang terjadi memaksa semua kelompok untuk melakukan pemikiran
ulang tentang tugas politik yang baru di era reformasi, terlebih khusus untuk
gereja, yakni bukan hanya melakukan kegiatan besar-besaran saja, tetapi
perlunya memikirkan arah, perspektif serta paradigma baru mengenai keterlibatan
gereja dalam politik. Dari latar belakang politik itu, analisis saya yang
pertama adalah di dalam dunia ‘perpolitikan’ tidak bisa lepas dari ‘komunikasi’
dan ‘kuasa’ itu sendiri, oleh karena kuasa merupakan aspek yang selalu muncul
baik dalam konteks komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi
antarorganisasi, maupun komunikasi massa adalah masalah kuasa.
Posisi
komunikasi sebagai pengantara di antara realita dan manusia membuatnya berkuasa
besar, baik di dalam memilih dan mendistorsi realita maupun dalam fungsinya
untuk menciptakan makna-makna baru di dalam hidup. Artinya, komunikasi sebagai
pengantara antara manusia dan realita menjadi “tuan besar”.[1]
PEMBAHASAN
Selama
ini terjadi kerancuan dan ambiguitas khususnya di dalam bidang sosial politik
di tengah kehidupan gereja-gereja di Indonesia. Pertanyaan yang selalu timbul
adalah apakah umat kristen boleh berpolitik atau tidak? Sampai batas manakah
umat Kristen masuk dalam dunia perpolitikan?, keadaan semacam itu justru sering
kali menimbulkan kebingungan dan kerawanan tertentu di masyarakat. Sikap
apatisme sering kali justru membuat orang tidak siap untuk mencari bentuk
tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Kita melihat akhir-akhir ini di
banyak gereja berkembang mempunyai pendapat bahwa para pendeta, pemimpin umat
dan para pemikir teologi tidak boleh menerjunkan diri ke dunia politik praktis,
tugas mereka yang utama adalah untuk menjembatani umat dengan dunia politik.
Dalam hal ini upaya untuk merumuskan “teologi kontekstual” di Indonesia selama
ini juga belum membuahkan hasil yang memuaskan.
Untuk
melakukan pembaruan politik bagi umat kristen, terlebih dahulu perlunya
meluruskan misperspepsi tentang politik, oleh karena pemahaman umat atau jemaat
tentang politik sering mengalami distorsi berdasarkan pengalaman-pengalaman
traumatik di masa lampau. Pemahaman itu biasanya bersifat menolak dan
mengkhawatirkan politik sebagai sumber kekacauan dan disharmoni, oleh karena
itu politik kemudian identik dengan kekacauan, perseturuan, persekongkolan dan
permusuhan. Politik dianggap kotor, lebih baik tidak menyentuhnya supaya orang
tidak dikotori dengan nafsu-nafsu jahat. Dengan pemahaman semacam itu timbulah
sikap apatisme dari kalangan masyarakat, sehingga mereka merasa tidak perlu
bertanggung jawab terhadap peraturan dalam dunia politik. Dari pandangan
tersebut, saya menanalisis bahwa yang terjadi adalah komunikasi itu seperti
prinsip ke 11 Deddy Mulyana yang mengatakan “Komunikasi bersifat Irreversible”,
yakni suatu perilaku atau suatu peristiwa, yang telah berlangsung dan tidak
dapat ‘diambil kembali’. Padahal, kemana pun orang menjauh dari politik, ia
tidak akan bisa terlalu jauh dari dunia politik. Pandangan semacam ini harus
diluruskan, harus dibuat keseimbangan
untuk melihat sisi politik yang sungguh manusiawi dan bersifat membebaskan.
Harus dikatakan bahwa politik bukanlah kotor, melainkan suci, atau paling tidak
tak bisa dihindari. Tugas gereja dalam politik adalah tugas suci, tugas khusus
yang tak bisa digantikan oleh lembaga lain di masyarakat. Politik itu suci,
karena tugas pokoknya adalah menjaga kesucian harkat dan martabat manusia yang
setiap hari dilangar dan dilecehkan dalam relasi-relasi yang tidak adil dalam
dunia politik.
Gereja-gereja
dalam konteks masa kini hanya berpikir tentang kepentingannya belaka. Mereka
hidup tanpa memperdulikan kepentingan orang lain untuk mencapai kedewasaan
dalam berpolitik. Tidak jarang warga gereja terjerumus dalam berbagai skenario
dan plot untuk memojokkan kelompok lain, sehingga sifat seperti itu cenderung
menolak pluralisme dan tidak memiliki pandangan politik yang lebih luas. Mereka
melakukan diskriminasi dan menghalangi orang lain ikut dalam kehidupan politik.
Seharusnya sebagai lembaga rohani yang terbuka, gereja juga harus mampu
melakukan otokritik untuk menilai diri seberapa jauh selama ini acapkali
tergoda untuk menjadi persekutuan yang tertutup merasa aman dalam lingkungan
benteng yang rapat terkunci.
Gereja
pada saat ini perlu diperbaharui juga, karena sebagai institus rohani yang
merupakan bagian integral masyarakat mengalami keadaan krisis juga, yakni
krisis kepemimpinan, institusional, keuangan dan juga kehilangan orientasi
teologi.Untuk melakukan perubahan tersebut, gereja harus melakukan pembaruan
politik ke arah emansipasi, yakni pembebasan atau permerdekaan. Emansipasi
politik perlu disadari selaku esensi keterlibatan gereja dalam reformasi
politik. Prinsip emansipasi berarti memberi peluangg dan kesediaan berbagi
kesempatan bagi kelompok lain untuk melakukan peran bagi kehidupan bersama di
tengah masyarakat majemuk. Pembaharuan politik merupakan upaya untuk mengubah
politik konfrontasi menjadi politik emansipasi. Dalam kaitan dengan hal itu,
panggilan dan peran gereja adalah menyiapkan sebuah landasan etika politik yang
lebih luas dan terbuka bagi umatnya, sambil menyebarluaskan gagasan keterbukaan
kepada masyarakat, dan berani mengambil inisiatif untuk melakukan komunikasi
dengan pemimpin umat yang lain. Gereja-gereja harus mengambil bagian yang nyata
pada upaya-upaya kelompok politik mana pun yang terarah pada pembentukan
masyarakat yang demokratis dan menghargai Hak Asasi Manusia (HAM).[2]
Gereja
saat ini terpangil untuk terbuka pada pilihan-pilian politik yang lebih
irasional dan memberi perhatian pada masa depan yang majemuk. Gereja-gereja
juga terpanggil untuk menawarkan wacana yang bisa diterima oleh masyarakat
luas, di mana kebanyakan warga masyarakat bisa mengambil bagian di dalamnya.
Wacana ini yang benar-benar bisa menjadi “medium komunikasi” yang menempatkan
semua pihak setara dan sekaligus menghargai integritas masin-masing. Dari buku Struggling In Hope sehubungan dengan
persoalan wacana tersebut, di tengah-tengah kemelut sosial-politik dewasa ini,
ada empat macam pilihan wacana di kalangan Kristen. Pertama, mereka yang
ingin mempertaruhkan wacana Kristen habis-habisan secara total frontal tanpa
kompromi. Secara prakttis dalam kehidupan politik mereka menerjemahkannya dengan
wadah partai politik Kristen, posisi ini bisa disebut eksklusif, karena dalam
posisi ini terdapat pemahaman bahwa kepentingan hanya dari kalangan Kristen. Kedua,
menawarkan sebuah wacana yang netral dan bercorak “sekuler” dengan cara langsung
menawarkan gagasan-gagasan yang bercorak “non agamis”, seperti demokrasi,
emansipasi, keadilan sosial, HAM, dan lain-lain. Pendekatan ini bisa disebut
sebagai pendekatan inklusif “sekuler” atau “netral agama”. Ketiga, adalah wacana
yang dikembangkan dari basis Pancasila sebagai salah satu puncak eksplorasi
konsensus politik yang ada dalam sejarah Indonesia. Pancasila yang dikenal
selaku pilihan kompromi antara sistem agama dan sistem sekuler merupakan jalan
tengah yang dibangun untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan dari
kelompok-kelompok suku dan agama. Keempat, yakni wacana yang
benar-benar terbuka bagi semua hal yang hidup dalam masyarakat, merupakan suatu
pendekatan yang bertolak dam berumara pada kemajemukan bangsa, khususnya
memberi perhatian pada agama-agama di Indonesia. Lebih khusus lagi memberi
perhatian kepada anutan agama mayoritas, dengan cara mendukung intrepretasinya
secara demokratis dan terbuka kepada umum. Posisi ini bisa disebut sebagai
wacana pluralisme, atau pluralisme religius.[3]
Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya jika keempat pilihan tersebut harus
dibicarakan secara kritis dan terbuka bagi gereja dan kelompok lain.
Untuk
menjalankan peran politik yang transformatif tersebut gereja-gereja tidak
mungkin hidup dalam kungkungan “kompleks minoritas”. Kompleks minoritas ini
bisa melahirkan dua macam ekstrem, yang pertama, hidup dalam ketakutan dan
kehilangan kepercayaan diri, kedua bisa muncul over kompensasi menentang
golongan lain dengan jalan kekerasan dan semangat martidom yang tinggi.
Sebagian umat Kristen fundamentalis mengambil sikap: lawan dan singkirkan
mereka dari arena politik! Dengan kompleks minoritas semacam itu tidak akan
mungkin terjadi dialog yang produktif dengan kalangan lain. Oleh karena itu
yang harus dikembangkan adalah solidaritas kritis dalam proses emansipasi
sosial-politik di mana semua pihak bisa menciptakan suatu suasana terbuka dan
memberi sumbangan dialogis terhadap masalah-masalah dasar masyarakat.
KESIMPULAN
Sebagai
kesimpulan, yakni gereja-gereja bersama dengan lembaga keagamaan lain tidak
boleh menyerahkan moral politik kepada elite politik belaka, yang dibutuhkan
adalah moral politik yang benar-benar menjaga harkat dan martabat manusia,
khususnya lapisan masyarakat di kalangan bawah yang selalu menjadi korban.
Keterlibatan lembaga keagamaan dalam politik adalah untuk menegakan dimensi
moral dalam politik. Politik tanpa moral akan selalu menghasilkan
penyalahgunaan kekuasaan untuk menindas sesama manusia. Gereja-gereja harus
menjadi penjaga yang efektif dalam dunia politik agar harga manusia tidak
direduksi dan didistorsi. Di sinilah tepatnya panggilan dan tugas gereja-gereja
untuk terbuka pada dialog (komunikasi dua arah) agar dapat menciptakan
kehidupan politik dengan landasan moral yang kuat, menjadi pengawal serta
harkat martabat manusia yang dipertaruhkan dalam praktik kehidupan politik
sehari-hari.
DAFTAR
PUSTAKA
1. Mulyana,
Deddy. Ilmu Komunikasi suatu pengantar.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya
2. Chandra,
Robby I. Teologi dan Komunikasi. Yogyakarta:
Duta Wacana University Press.
3. Bergumul
dalam pengharapan. Jakarta: Gunung Mulia, 2004.



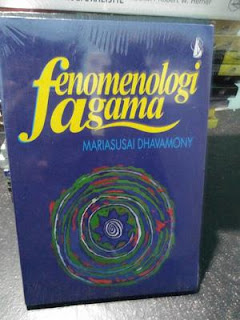
Comments
Post a Comment